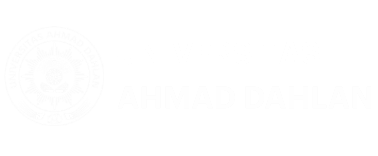84 Tahun Sumpah Pemuda

Oleh: Sudaryanto, M.Pd.
Dosen PBSI FKIP UAD Yogyakarta
Jakarta, 28 Oktober 1928. Para pemuda dari pelbagai daerah di Nusantara telah berkumpul. Ada Jong Java, Jong Sumatra, Jong Celebes, dan sebagainya. Mereka berkumpul dalam Kongres Pemuda II, dan lantas mengikrarkan diri ke dalam satu simpul pengakuan: Sumpah Pemuda. Alangkah hafalnya kita akan isi sumpah tersebut; namun alangkah sulitnya untuk mengimplementasikan ke dalam perbuatan sehari-hari.
Kini, setelah 84 tahun berlalu, gema dari ketiga butir dalam Sumpah Pemuda itu terdengar lamat-lamat, bahkan nyaris sunyi. Pada butir pertama yang berbunyi asli “Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah Darah jang satoe, Tanah Indonesia”, segera terbayang betapa perjuangan para pemuda saat itu luar biasa. Mereka berani menanggalkan baju kedaerahan dan perbedaan yang ada, berganti dengan baju keindonesiaan yang utuh.
Pada butir kedua dan ketiga yang berbunyi asli, “Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa Jang satoe, bangsa Indonesia”, dan “Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng Bahasa persatoean, bahasa Indonesia”, pun terbayang lagi perjuangan pemuda saat itu. Sebuah perjuangan yang saya kira betul-betul ikhlas, serta membawa pengaruh besar bagi gerak kemajuan bangsa ini di masa-masa berikutnya.
Tapi kini, apa mau dikata. Alih-alih gerak maju, justru bangsa ini mengalami gerak mundur pelan-pelan. Bangsa ini lambat laun, seperti disindir oleh Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), menjadi gelandang di rumah sendiri. Betapa tidak! Kita dianugerahi sebuah negeri yang kaya raya, tapi kita malas untuk mengelolanya. Akhirnya, atas kemalasan itu kita tawarkan kepada pihak asing untuk mengelolanya.
Sayangnya, pihak asing itu tidak mengelolanya dengan amanah dan profesional sehingga kerugianlah yang kita derita saat ini. Lewat tulisan ini, kita perlu menyerukan agar para pemimpin kita tidak lagi menggelar karpet merah bagi pihak asing mana pun. Saya yakin, apabila pemimpin bangsa ini amanah dan profesional dalam mengelola sumber daya alam (SDA) yang ada, kelak kesejahteraan hidup tidak lagi menjadi mimpi di siang bolong bagi kita.
Di sisi lain, kita patut prihatin dengan makin maraknya aksi kekerasan, termasuk aksi tawuran pelajar yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Lebih ironis, ternyata pelaku kekerasan itu ialah para pelajar yang merupakan generasi muda bangsa. Bisa Anda bayangkan, betapa bangsa ini akan selalu terjerumus ke dalam tindak kekerasan massa ketika menghadapi dinding perbedaan. Entah itu pilihan politik, agama, status sosial, atau yang lainnya.
Apabila momentum Kongres Pemuda II itu kita tapak-tilasi kembali, seyogianya semua perbedaan yang ada dapat diterima dengan lapang. Pasalnya, sekali lagi mengutip Cak Nun, yang harus kita cari itu esensi, bukan eksistensi. Para pemuda yang hadir dalam Kongres Pemuda II saat itu, jelas-jelas berbeda suku, bahasa, dan agama; namun tekad mereka satu: ingin mencari esensi dalam wadah yang bernama Indonesia.
Akhirnya, melalui momentum Hari Sumpah Pemuda, semoga kita selaku warga bangsa tergerak hati untuk kembali merefleksikan seberapa besar komitmen kita untuk bangsa-negara tercinta ini. Paling tidak, hal itu kita mulai dari seberapa besar cinta kita dalam menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari, juga mengikhlaskan diri demi kepentingan bangsa. Itulah esensi keindonesiaan yang perlu kita tumbuhkan mulai hari ini. Selamat Hari Sumpah Pemuda![]

Oleh: Sudaryanto, M.Pd.
Dosen PBSI FKIP UAD Yogyakarta
Jakarta, 28 Oktober 1928. Para pemuda dari pelbagai daerah di Nusantara telah berkumpul. Ada Jong Java, Jong Sumatra, Jong Celebes, dan sebagainya. Mereka berkumpul dalam Kongres Pemuda II, dan lantas mengikrarkan diri ke dalam satu simpul pengakuan: Sumpah Pemuda. Alangkah hafalnya kita akan isi sumpah tersebut; namun alangkah sulitnya untuk mengimplementasikan ke dalam perbuatan sehari-hari.
Kini, setelah 84 tahun berlalu, gema dari ketiga butir dalam Sumpah Pemuda itu terdengar lamat-lamat, bahkan nyaris sunyi. Pada butir pertama yang berbunyi asli “Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah Darah jang satoe, Tanah Indonesia”, segera terbayang betapa perjuangan para pemuda saat itu luar biasa. Mereka berani menanggalkan baju kedaerahan dan perbedaan yang ada, berganti dengan baju keindonesiaan yang utuh.
Pada butir kedua dan ketiga yang berbunyi asli, “Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa Jang satoe, bangsa Indonesia”, dan “Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng Bahasa persatoean, bahasa Indonesia”, pun terbayang lagi perjuangan pemuda saat itu. Sebuah perjuangan yang saya kira betul-betul ikhlas, serta membawa pengaruh besar bagi gerak kemajuan bangsa ini di masa-masa berikutnya.
Tapi kini, apa mau dikata. Alih-alih gerak maju, justru bangsa ini mengalami gerak mundur pelan-pelan. Bangsa ini lambat laun, seperti disindir oleh Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), menjadi gelandang di rumah sendiri. Betapa tidak! Kita dianugerahi sebuah negeri yang kaya raya, tapi kita malas untuk mengelolanya. Akhirnya, atas kemalasan itu kita tawarkan kepada pihak asing untuk mengelolanya.
Sayangnya, pihak asing itu tidak mengelolanya dengan amanah dan profesional sehingga kerugianlah yang kita derita saat ini. Lewat tulisan ini, kita perlu menyerukan agar para pemimpin kita tidak lagi menggelar karpet merah bagi pihak asing mana pun. Saya yakin, apabila pemimpin bangsa ini amanah dan profesional dalam mengelola sumber daya alam (SDA) yang ada, kelak kesejahteraan hidup tidak lagi menjadi mimpi di siang bolong bagi kita.
Di sisi lain, kita patut prihatin dengan makin maraknya aksi kekerasan, termasuk aksi tawuran pelajar yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Lebih ironis, ternyata pelaku kekerasan itu ialah para pelajar yang merupakan generasi muda bangsa. Bisa Anda bayangkan, betapa bangsa ini akan selalu terjerumus ke dalam tindak kekerasan massa ketika menghadapi dinding perbedaan. Entah itu pilihan politik, agama, status sosial, atau yang lainnya.
Apabila momentum Kongres Pemuda II itu kita tapak-tilasi kembali, seyogianya semua perbedaan yang ada dapat diterima dengan lapang. Pasalnya, sekali lagi mengutip Cak Nun, yang harus kita cari itu esensi, bukan eksistensi. Para pemuda yang hadir dalam Kongres Pemuda II saat itu, jelas-jelas berbeda suku, bahasa, dan agama; namun tekad mereka satu: ingin mencari esensi dalam wadah yang bernama Indonesia.
Akhirnya, melalui momentum Hari Sumpah Pemuda, semoga kita selaku warga bangsa tergerak hati untuk kembali merefleksikan seberapa besar komitmen kita untuk bangsa-negara tercinta ini. Paling tidak, hal itu kita mulai dari seberapa besar cinta kita dalam menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari, juga mengikhlaskan diri demi kepentingan bangsa. Itulah esensi keindonesiaan yang perlu kita tumbuhkan mulai hari ini. Selamat Hari Sumpah Pemuda![]