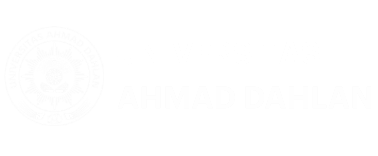Bahasa Indonesia, Wow Begitu?!
Saya tiba-tiba teringat pada beberapa sosok Indonesianis, seperti A. Teeuw, Harry Aveling, Keith Foulcher, Greg Barton, hingga George M. Kahin. Meski mereka bukan warga pribumi (baca: WNI), namun mereka mencintai negara ini. Buktinya, mereka bisa berbahasa Indonesia dan menggunakannya secara baik. Dalam batas tertentu, mereka jauh lebih “meng-Indonesia” ketimbang diri kita. Mengapa demikian?
Menyebut nama A. Teeuw, Harry Aveling, dan Keith Foulcher dalam satu tarikan napas, berarti pula menyebut jasa-jasanya terhadap sastra Indonesia. Mendiang A. Teeuw ialah guru besar bidang kesusasteraan Indonesia modern pada Universitas Leiden, Belanda. Sementara itu, Harry Aveling merupakan pakar sastra Indonesia di La Trobe University, Australia, dan Keith Foulcher di bidang yang sama di Sydney University, Australia.
Kepakaran ketiganya di bidang sastra Indonesia sudah tak diragukan lagi. Berbagai karya bukunya dijadikan rujukan oleh para dosen, peneliti, dan mahasiswa sastra Indonesia. Saat menyusun disertasi doktoral (S-3), mereka pun sungguh-sungguh belajar bahasa Indonesia. Tak ayal jika mereka begitu mahir dalam menulis karya-karya tentang kesusasteraan Indonesia, termasuk pula membimbing penelitian para dosen kita.
Dua nama berikutnya, Greg Barton dan George M. Kahin, juga pakar di bidangnya masing-masing. Barton lebih dikenal sebagai pakar kajian Asia Tenggara di Monash University, Australia, sedangkan Kahin merupakan guru besar Cornell University, AS. Seperti ketiga nama di atas, baik Barton maupun Kahin juga menulis disertasi tentang Indonesia. Sebelum itu, mereka pun sungguh-sungguh belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa sumber penelitiannya.
Bahkan, dalam wawancaranya di sebuah harian nasional baru-baru ini, Greg Barton mengaku lebih senang berbahasa Indonesia dengan istri dan anaknya. Kata Barton, untuk menyampaikan hal yang sifatnya rahasia di tengah orang-orang Australia kami menggunakan bahasa Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Greg Barton, juga keempat Indonesianis di atas, menjadi bukti yang tak terbantahkan tentang pesona bahasa (dan sastra) Indonesia yang luar biasa.
Alih-alih pesona bahasa Indonesia itu luar biasa, justru kita menganggapnya biasa-biasa saja. Seolah tak ada yang istimewa, bahkan kita pun cenderung tidak bangga berbahasa Indonesia. Ketidakbanggaan kita tecermin pada ucapan-ucapan sehari-hari yang cenderung mencampuradukkan bahasa asing dan bahasa Indonesia. Gejala ini saya sebut dengan istilah “Indoenglish”. Entah lazim atau tidak, fenomena “Indoenglish” kian kental di lidah kita sekarang.
Pada gilirannya, saya menduga akan terjadi ketidakbanggaan berbahasa Indonesia pada diri kita di masa-masa mendatang. Padahal, orang-orang asing, termasuk kelima Indonesianis di atas, sangat mencintai bahasa Indonesia. Untuk itu, marilah kita giatkan dan tumbuhkan perasaan cinta terhadap bahasa Indonesia. Dengan cara begitu, kita akan “meng-Indonesia” seperti halnya kelima Indonesianis tadi.
Akhirnya, semoga kita dapat menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, serta penuh kebanggaan. Tak ada artinya kebanggaan tanpa kepedulian; dan tak ada artinya kepedulian tanpa rasa cinta. Mencintai bahasa Indonesia itu berbanding lurus dengan mencintai tanah air, bangsa, dan negara ini. Jika tidak ada rasa cinta, lantas kita sendiri akan berujar dengan nada sarkastis, “Bahasa Indonesia wow begitu?!” Semoga tidak![]
Saya tiba-tiba teringat pada beberapa sosok Indonesianis, seperti A. Teeuw, Harry Aveling, Keith Foulcher, Greg Barton, hingga George M. Kahin. Meski mereka bukan warga pribumi (baca: WNI), namun mereka mencintai negara ini. Buktinya, mereka bisa berbahasa Indonesia dan menggunakannya secara baik. Dalam batas tertentu, mereka jauh lebih “meng-Indonesia” ketimbang diri kita. Mengapa demikian?
Menyebut nama A. Teeuw, Harry Aveling, dan Keith Foulcher dalam satu tarikan napas, berarti pula menyebut jasa-jasanya terhadap sastra Indonesia. Mendiang A. Teeuw ialah guru besar bidang kesusasteraan Indonesia modern pada Universitas Leiden, Belanda. Sementara itu, Harry Aveling merupakan pakar sastra Indonesia di La Trobe University, Australia, dan Keith Foulcher di bidang yang sama di Sydney University, Australia.
Kepakaran ketiganya di bidang sastra Indonesia sudah tak diragukan lagi. Berbagai karya bukunya dijadikan rujukan oleh para dosen, peneliti, dan mahasiswa sastra Indonesia. Saat menyusun disertasi doktoral (S-3), mereka pun sungguh-sungguh belajar bahasa Indonesia. Tak ayal jika mereka begitu mahir dalam menulis karya-karya tentang kesusasteraan Indonesia, termasuk pula membimbing penelitian para dosen kita.
Dua nama berikutnya, Greg Barton dan George M. Kahin, juga pakar di bidangnya masing-masing. Barton lebih dikenal sebagai pakar kajian Asia Tenggara di Monash University, Australia, sedangkan Kahin merupakan guru besar Cornell University, AS. Seperti ketiga nama di atas, baik Barton maupun Kahin juga menulis disertasi tentang Indonesia. Sebelum itu, mereka pun sungguh-sungguh belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa sumber penelitiannya.
Bahkan, dalam wawancaranya di sebuah harian nasional baru-baru ini, Greg Barton mengaku lebih senang berbahasa Indonesia dengan istri dan anaknya. Kata Barton, untuk menyampaikan hal yang sifatnya rahasia di tengah orang-orang Australia kami menggunakan bahasa Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Greg Barton, juga keempat Indonesianis di atas, menjadi bukti yang tak terbantahkan tentang pesona bahasa (dan sastra) Indonesia yang luar biasa.
Alih-alih pesona bahasa Indonesia itu luar biasa, justru kita menganggapnya biasa-biasa saja. Seolah tak ada yang istimewa, bahkan kita pun cenderung tidak bangga berbahasa Indonesia. Ketidakbanggaan kita tecermin pada ucapan-ucapan sehari-hari yang cenderung mencampuradukkan bahasa asing dan bahasa Indonesia. Gejala ini saya sebut dengan istilah “Indoenglish”. Entah lazim atau tidak, fenomena “Indoenglish” kian kental di lidah kita sekarang.
Pada gilirannya, saya menduga akan terjadi ketidakbanggaan berbahasa Indonesia pada diri kita di masa-masa mendatang. Padahal, orang-orang asing, termasuk kelima Indonesianis di atas, sangat mencintai bahasa Indonesia. Untuk itu, marilah kita giatkan dan tumbuhkan perasaan cinta terhadap bahasa Indonesia. Dengan cara begitu, kita akan “meng-Indonesia” seperti halnya kelima Indonesianis tadi.
Akhirnya, semoga kita dapat menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, serta penuh kebanggaan. Tak ada artinya kebanggaan tanpa kepedulian; dan tak ada artinya kepedulian tanpa rasa cinta. Mencintai bahasa Indonesia itu berbanding lurus dengan mencintai tanah air, bangsa, dan negara ini. Jika tidak ada rasa cinta, lantas kita sendiri akan berujar dengan nada sarkastis, “Bahasa Indonesia wow begitu?!” Semoga tidak![]