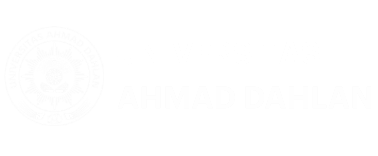AKADEMIA REPUBLIKA INDONESIA MINUS DOKUMENTASI BAHASA
Oleh: Sudaryanto, M.Pd.
Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UAD Yogyakarta
Judul tulisan ini mirip dengan judul berita yang pernah muncul di sebuah harian nasional beberapa hari lalu. Penulis sengaja menggunakannya, tanpa mengubah sedikit pun dengan beberapa alasan. Sekurangnya, ada dua alasan yang mendasar, yaitu pertama, judul itu dibaca sebagai realitas/kenyataan yang saat ini sedang terjadi, dan kedua, judul itu pula dibaca sebagai tantangan yang mestinya dijawab dengan komitmen dan perbuatan. Dengan kedua alasan itu, kita akan terhindar dari kemungkinan yang terburuk: Indonesia darurat dokumentasi bahasa.
Alasan pertama, yakni bahwa Indonesia dipandang minus dokumentasi bahasa. Pandangan ini muncul dari RMT Multamia Lauder, seorang guru besar bidang bahasa dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (UI). Sebagai orang yang menaruh minat pada bidang sosiolinguistik, khususnya etnolinguistik, Multamia Lauder seolah mengingatkan kita tentang betapa pentingnya dokumentasi bahasa, khususnya bahasa-bahasa daerah yang kondisinya terancam mengalami kepunahan.
Terkait itu, dalam sebuah edisinya, majalah Tempo pernah menurunkan liputan tentang aktivitas para peneliti LIPI yang terjun ke wilayah-wilayah di Indonesia bagian timur, seperti Flores, Maluku, dan Papua. Diberitakan, bahwa di daerah Flores ada satu dialek bahasa daerah yang penuturnya tinggal seorang diri. Bisa dibayangkan jika penutur tadi suatu waktu meninggal dunia, dialek bahasa daerah itu pun hilang. Makanya para peneliti LIPI dengan usahanya yang tak kenal menyerah, mencatat dan merekam dialek bahasa tersebut.
Namun, catatan tinggal catatan; rekaman tinggal rekaman, ternyata kaset yang digunakan untuk merekam tidak terawat dengan baik. Alih-alih dirawat, justru dibiarkan rusak dengan sendirinya. Alhasil, usaha yang telah dilakukan oleh para peneliti LIPI menjadi sia-sia, muspra. Kejadian ini pun mengingatkan kita pada berita tidak terawatnya dokumentasi sastra pada Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin, beberapa waktu lalu. Jika tak salah ingat, Pemerintah DKI Jakarta saat itu sudah tidak lagi mengucurkan dana perawatan bagi PDS HB Jassin.
Alasan kedua, yakni bahwa Indonesia dipandang minus dokumentasi bahasa. Pandangan ini mestinya dipahami sebagai suatu tantangan yang perlu dijawab dengan komitmen dan perbuatan, terutama oleh/dari pemerintah pusat dan daerah. Selama ini, jujur saja, nasib bahasa daerah ditentukan oleh penuturnya sendiri. Seolah pemerintah daerah menutup mata terhadap kewajibannya untuk membina, mengembangkan, dan melestarikan bahasa daerahnya masing-masing. Padahal, hal tersebut telah diatur dalam konstitusi.
Bahasa Jawa, misalnya, sebagai bahasa yang memiliki jumlah penutur sangat banyak dan beragam dialek itu, namun belum tentu aman dari ancaman kepunahan. Selama ini, yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah barulah pada tahap pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bahasa Jawa, tidak lebih dari itu. Terlepas dari kenyataan betapa banyak siswa yang tidak berminat menggunakan bahasa Jawa, hal itu menjadi kenyataan yang tidak bisa ditutup-tutupi. Entahlah, apakah pemerintah daerah terbuka matanya akan hal tersebut.
Sementara itu, penerbitan karya-karya sastra daerah, khususnya sastra Jawa, berjalan tersendat-sendat. Untungnya Ajip Rosidi melalui Yayasan Rancage-nya, juga Rachmat Djoko Pradopo melalui Yasayo-nya, memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap pengarang-pengarang yang setia berkarya sastra dengan bahasa daerah (Jawa, Sunda, dan Bali). Meski bersifat nonprofit, juga nonpartisan partai politik, kedua yayasan tersebut secara rutin memberikan penghargaan bagi pengarang-pengarang sastra daerah.
Kita telah memiliki Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin yang dibangun dengan susah payah oleh almarhum HB Jassin. Sebagai bentuk penghormatan kepada jasa-jasanya, selayaknya pusat dokumentasi tersebut kita jaga sepenuh hati. Pun, jika kita nantinya memiliki pusat dokumentasi sekelas PDS HB Jassin, maka kita jaga pula sepenuh hati. Jika tidak, pada tahun 2045 mendatang bahasa-bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, Sunda, Dayak, hingga Flores hanya akan dapat kita jumpai dalam museum bahasa yang bisu dan pengap.[]
Oleh: Sudaryanto, M.Pd.
Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UAD Yogyakarta
Judul tulisan ini mirip dengan judul berita yang pernah muncul di sebuah harian nasional beberapa hari lalu. Penulis sengaja menggunakannya, tanpa mengubah sedikit pun dengan beberapa alasan. Sekurangnya, ada dua alasan yang mendasar, yaitu pertama, judul itu dibaca sebagai realitas/kenyataan yang saat ini sedang terjadi, dan kedua, judul itu pula dibaca sebagai tantangan yang mestinya dijawab dengan komitmen dan perbuatan. Dengan kedua alasan itu, kita akan terhindar dari kemungkinan yang terburuk: Indonesia darurat dokumentasi bahasa.
Alasan pertama, yakni bahwa Indonesia dipandang minus dokumentasi bahasa. Pandangan ini muncul dari RMT Multamia Lauder, seorang guru besar bidang bahasa dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (UI). Sebagai orang yang menaruh minat pada bidang sosiolinguistik, khususnya etnolinguistik, Multamia Lauder seolah mengingatkan kita tentang betapa pentingnya dokumentasi bahasa, khususnya bahasa-bahasa daerah yang kondisinya terancam mengalami kepunahan.
Terkait itu, dalam sebuah edisinya, majalah Tempo pernah menurunkan liputan tentang aktivitas para peneliti LIPI yang terjun ke wilayah-wilayah di Indonesia bagian timur, seperti Flores, Maluku, dan Papua. Diberitakan, bahwa di daerah Flores ada satu dialek bahasa daerah yang penuturnya tinggal seorang diri. Bisa dibayangkan jika penutur tadi suatu waktu meninggal dunia, dialek bahasa daerah itu pun hilang. Makanya para peneliti LIPI dengan usahanya yang tak kenal menyerah, mencatat dan merekam dialek bahasa tersebut.
Namun, catatan tinggal catatan; rekaman tinggal rekaman, ternyata kaset yang digunakan untuk merekam tidak terawat dengan baik. Alih-alih dirawat, justru dibiarkan rusak dengan sendirinya. Alhasil, usaha yang telah dilakukan oleh para peneliti LIPI menjadi sia-sia, muspra. Kejadian ini pun mengingatkan kita pada berita tidak terawatnya dokumentasi sastra pada Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin, beberapa waktu lalu. Jika tak salah ingat, Pemerintah DKI Jakarta saat itu sudah tidak lagi mengucurkan dana perawatan bagi PDS HB Jassin.
Alasan kedua, yakni bahwa Indonesia dipandang minus dokumentasi bahasa. Pandangan ini mestinya dipahami sebagai suatu tantangan yang perlu dijawab dengan komitmen dan perbuatan, terutama oleh/dari pemerintah pusat dan daerah. Selama ini, jujur saja, nasib bahasa daerah ditentukan oleh penuturnya sendiri. Seolah pemerintah daerah menutup mata terhadap kewajibannya untuk membina, mengembangkan, dan melestarikan bahasa daerahnya masing-masing. Padahal, hal tersebut telah diatur dalam konstitusi.
Bahasa Jawa, misalnya, sebagai bahasa yang memiliki jumlah penutur sangat banyak dan beragam dialek itu, namun belum tentu aman dari ancaman kepunahan. Selama ini, yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah barulah pada tahap pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bahasa Jawa, tidak lebih dari itu. Terlepas dari kenyataan betapa banyak siswa yang tidak berminat menggunakan bahasa Jawa, hal itu menjadi kenyataan yang tidak bisa ditutup-tutupi. Entahlah, apakah pemerintah daerah terbuka matanya akan hal tersebut.
Sementara itu, penerbitan karya-karya sastra daerah, khususnya sastra Jawa, berjalan tersendat-sendat. Untungnya Ajip Rosidi melalui Yayasan Rancage-nya, juga Rachmat Djoko Pradopo melalui Yasayo-nya, memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap pengarang-pengarang yang setia berkarya sastra dengan bahasa daerah (Jawa, Sunda, dan Bali). Meski bersifat nonprofit, juga nonpartisan partai politik, kedua yayasan tersebut secara rutin memberikan penghargaan bagi pengarang-pengarang sastra daerah.
Kita telah memiliki Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin yang dibangun dengan susah payah oleh almarhum HB Jassin. Sebagai bentuk penghormatan kepada jasa-jasanya, selayaknya pusat dokumentasi tersebut kita jaga sepenuh hati. Pun, jika kita nantinya memiliki pusat dokumentasi sekelas PDS HB Jassin, maka kita jaga pula sepenuh hati. Jika tidak, pada tahun 2045 mendatang bahasa-bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, Sunda, Dayak, hingga Flores hanya akan dapat kita jumpai dalam museum bahasa yang bisu dan pengap.[]