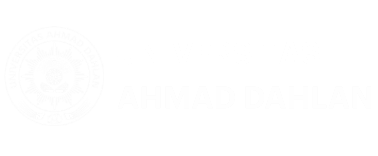PEMBELAJARAN SASTRA DIANAKTIRIKAN
Oleh: Sudaryanto, M.Pd.
Dosen PBSI FKIP UAD Yogyakarta
Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Pardi Suratno menyampaikan pernyataan yang menarik. Ia menyatakan, pembelajaran sastra di sekolah selama ini masih menjadi pelajaran “kelas dua”, setelah pembelajaran bahasa Indonesia. “Pembelajaran sastra Indonesia, termasuk puisi di sekolah-sekolah perlu ditingkatkan,” katanya, saat acara pergelaran Lomba Cipta Puisi Indonesia dan Jawa di Semarang, Minggu (21/10) lalu.
Jauh sebelum itu, penyair yang juga guru besar ilmu sastra dari Universitas Negeri Yogyakarta, Suminto A. Sayuti, mengungkapkan, pembelajaran sastra di sekolah selama ini terkesan menyebalkan. Ungkapan itu penulis dengar tatkala mengikuti acara Apresiasi Sastra Daerah (Apresda) bagi para guru bahasa Indonesia tingkat SMA se-Indonesia di Cisarua, Bogor, dua tahun silam. Saat itu, ajaibnya, ungkapan Profesor Suminto itu kami setujui meski menyesakkan dada.
Betapa tidak, pembelajaran sastra yang semestinya memerdekakan siswa dan guru, ternyata sebaliknya. Di sekolah atau madrasah kita, pembelajaran sastra belum menjadi mata pelajaran yang disenangi oleh siswa. Para siswa hanya dicekoki oleh materi-materi tentang nama sastrawan, judul-judul karya sastra, dan angkatan dalam sastra Indonesia. Sementara itu, minat membaca dan menulis karya sastra di kalangan guru masih rendah.
Kondisi di atas, jika ditambah lagi dengan persoalan minimnya ketersediaan buku-buku sastra di perpustakaan sekolah, tentunya makin membuat hati kita miris. Melihat hal tersebut, kiranya kita tak bijak menyalahkan guru sebagai pihak yang menyebabkan pembelajaran sastra dianaktirikan ketimbang pembelajaran bahasa. Untuk itu, kita perlu mencari langkah-langkah yang jitu guna meningkatkan kualitas pembelajaran sastra di sekolah lebih baik lagi.
Pertama, pola pembelajaran sastra diarahkan sebisa mungkin tidak bersifat teoretis, tetapi lebih bersifat apresiatif. Para guru dapat mengajak para siswanya untuk berkunjung ke perpustakaan daerah atau komunitas sastra di daerah. Kunjungan itu dapat dirutinkan seminggu atau sebulan sekali. Dengan cara begitu, daya apresiasi para siswa terhadap karya sastra diharapkan dapat meningkat, bahkan ke tahap penciptaan karya sastra yang unik dan menarik.
Kedua, para guru dapat mengambil bahan ajar sastra dari media massa lokal dan/atau nasional. Semua koran edisi Minggu biasanya memuat rubrik cerpen, puisi, dan esai budaya/sastra. Menurut hemat saya, kesemua rubrik itu dapat didayagunakan untuk pembelajaran sastra, sembari dipikirkan ulang mengenai pemahaman para siswa terhadap isi cerpen, puisi, dan esai budaya/sastra. Jadi, bahan ajar sastra tidak harus dari buku pelajaran yang ada.
Ketiga, saat pembelajaran sastra berlangsung para siswa dapat diajak ke luar kelas, seperti taman sekolah. Sebagai guru, kita berikan kebebasan kepada siswa-siswa untuk mengembangkan imajinasinya dengan cara menulis karya sastra. Para siswa diajak untuk merasakan desir angin yang berhembus, harumnya wangi bunga, teriknya sinar matahari, dan gejala alam lainnya. Dengan merasakan itu semua, kelak imajinasi para siswa dapat berkembang.
Dengan langkah-langkah di atas, kiranya kondisi pembelajaran sastra yang selama ini dianaktirikan dapat diubah menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan hal itu, mau tidak mau, semua pihak memiliki peran yang sama. Para guru didorong untuk “rangkap jabatan”: sebagai pendidik sekaligus penulis sastra yang mumpuni. Pula, pihak sekolah dapat menyediakan bahan bacaan karya sastra yang lengkap di perpustakaan. Saya optimis hal itu terwujud, Anda juga? Semoga.[]
Oleh: Sudaryanto, M.Pd.
Dosen PBSI FKIP UAD Yogyakarta
Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Pardi Suratno menyampaikan pernyataan yang menarik. Ia menyatakan, pembelajaran sastra di sekolah selama ini masih menjadi pelajaran “kelas dua”, setelah pembelajaran bahasa Indonesia. “Pembelajaran sastra Indonesia, termasuk puisi di sekolah-sekolah perlu ditingkatkan,” katanya, saat acara pergelaran Lomba Cipta Puisi Indonesia dan Jawa di Semarang, Minggu (21/10) lalu.
Jauh sebelum itu, penyair yang juga guru besar ilmu sastra dari Universitas Negeri Yogyakarta, Suminto A. Sayuti, mengungkapkan, pembelajaran sastra di sekolah selama ini terkesan menyebalkan. Ungkapan itu penulis dengar tatkala mengikuti acara Apresiasi Sastra Daerah (Apresda) bagi para guru bahasa Indonesia tingkat SMA se-Indonesia di Cisarua, Bogor, dua tahun silam. Saat itu, ajaibnya, ungkapan Profesor Suminto itu kami setujui meski menyesakkan dada.
Betapa tidak, pembelajaran sastra yang semestinya memerdekakan siswa dan guru, ternyata sebaliknya. Di sekolah atau madrasah kita, pembelajaran sastra belum menjadi mata pelajaran yang disenangi oleh siswa. Para siswa hanya dicekoki oleh materi-materi tentang nama sastrawan, judul-judul karya sastra, dan angkatan dalam sastra Indonesia. Sementara itu, minat membaca dan menulis karya sastra di kalangan guru masih rendah.
Kondisi di atas, jika ditambah lagi dengan persoalan minimnya ketersediaan buku-buku sastra di perpustakaan sekolah, tentunya makin membuat hati kita miris. Melihat hal tersebut, kiranya kita tak bijak menyalahkan guru sebagai pihak yang menyebabkan pembelajaran sastra dianaktirikan ketimbang pembelajaran bahasa. Untuk itu, kita perlu mencari langkah-langkah yang jitu guna meningkatkan kualitas pembelajaran sastra di sekolah lebih baik lagi.
Pertama, pola pembelajaran sastra diarahkan sebisa mungkin tidak bersifat teoretis, tetapi lebih bersifat apresiatif. Para guru dapat mengajak para siswanya untuk berkunjung ke perpustakaan daerah atau komunitas sastra di daerah. Kunjungan itu dapat dirutinkan seminggu atau sebulan sekali. Dengan cara begitu, daya apresiasi para siswa terhadap karya sastra diharapkan dapat meningkat, bahkan ke tahap penciptaan karya sastra yang unik dan menarik.
Kedua, para guru dapat mengambil bahan ajar sastra dari media massa lokal dan/atau nasional. Semua koran edisi Minggu biasanya memuat rubrik cerpen, puisi, dan esai budaya/sastra. Menurut hemat saya, kesemua rubrik itu dapat didayagunakan untuk pembelajaran sastra, sembari dipikirkan ulang mengenai pemahaman para siswa terhadap isi cerpen, puisi, dan esai budaya/sastra. Jadi, bahan ajar sastra tidak harus dari buku pelajaran yang ada.
Ketiga, saat pembelajaran sastra berlangsung para siswa dapat diajak ke luar kelas, seperti taman sekolah. Sebagai guru, kita berikan kebebasan kepada siswa-siswa untuk mengembangkan imajinasinya dengan cara menulis karya sastra. Para siswa diajak untuk merasakan desir angin yang berhembus, harumnya wangi bunga, teriknya sinar matahari, dan gejala alam lainnya. Dengan merasakan itu semua, kelak imajinasi para siswa dapat berkembang.
Dengan langkah-langkah di atas, kiranya kondisi pembelajaran sastra yang selama ini dianaktirikan dapat diubah menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan hal itu, mau tidak mau, semua pihak memiliki peran yang sama. Para guru didorong untuk “rangkap jabatan”: sebagai pendidik sekaligus penulis sastra yang mumpuni. Pula, pihak sekolah dapat menyediakan bahan bacaan karya sastra yang lengkap di perpustakaan. Saya optimis hal itu terwujud, Anda juga? Semoga.[]