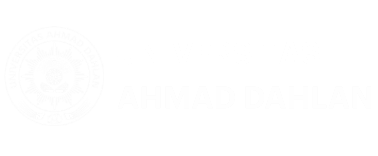Membenahi Kekeliruan Presidential Threshold
Dani Fadillah*
Kala bangsa ini memerlukan sosok pemimpin alternatif yang dapat membawa bangsa ini keluar dari keterpurukan, sebuah fenomena unik terjadi, yaitu kesibukan anggota-anggota dewan di DPR yang tengah menggodok sebuah kebijakan yang menjurus pada seolah kualitas presiden ditentukan oleh besar-kecilnya dukungan parpol atas calon presiden. layaknya Pemilu Presiden 2009 dimana seseorang hanya bisa dicalonkan menjadi presiden dan wakilnya ketika mendapat dukungan paling sedikit 25% dari partai-partai pendukungnya secara nasional atau 20% kursi DPR. Kebijakan ini tertuang dalam UU No 42/2008 dan saat ini tengah diperbicangkan secara transaksional oleh DPR apakah persentasenya dikurangi atau malah diperbesar. Sebuah kebijakan yang menurut hemat penulis seharusnya tidak perlu dipersoalkan, lebih baik jika kebijakan itu dihilangkan saja.
Karena pemberlakuan ambang batas tertentu dalam pencalonan presiden sungguh tidak dapat diterima oleh akal sehat maupun dari segi kacamata politik. Begini, basis legitimasi presiden dalam sebuah negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Presiden dan parlemen adalah dua institusi yang berbeda dan memiliki basis legitimasi yang berbeda pula.
Singkat kata, pemberlakuan presidential threshold tidak dapat dijadikan sebagai standar batasan untuk pencalonan seseorang menjadi presiden nmaun dalam rangka menentukan persentase suara minimum sang calon presiden dinyatakan sahtelah terpilih untuk menjabat selama satu periode kedepan. Di Indonesia, kebijakan presidential threshold ini sudah sangat jelas bahwa Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Simpel, bukan?
Kebijakan tidak perlu semacam ini tidak perlu muncul seandainya para elit parpol tidak terperangkap ke dalam egoisme mereka. Beberapa partai besar mengusulkan ambang batas pencalonan presiden yang relatif tinggi karena terlalu percaya diri dengan elektabilitas masing-masing calon yang hendah mereka jagokan melalui hasil laporan lembaga survey kepercayaan mereka.
Dapat dikatakan tidak ada satupun elit partai yang berbicara soal kebutuhan kepemimpinan nasional dalam konteks krusial dan strategis untuk bangsa kita kedepan. Dan sangat minim ada parpol yang dengan jumawa mau mengakui ada sosok yang lebih oantas untuk memimpin bangsa ini yang berada diluar partainya jabatan sebagai ketua umum partai dengan dukungan matematis diatas kertas adalah syarat sah seseorang dicalonkan untuk menjadi presiden, bukan kualitas secara hakiki yang diakui dengan ksatria secara komunal.dan ujung-ujungnya Pilpres tak ubahnya ladang adu banyak uang untuk meraup suara sebanyak-banyaknya antar ketua umum parpol. Dalam pemaparan visi dan misi juga tidak akan diperjuangkan oleh masing-masing kandidat, dalam forum-forum debatpun hanya akan menjadi bumbu bahwa sekarang sedang dalam suasana pilpres.
Sungguh sangat mahal ongkos sosial dan politik yang harus ditanggung bansa ini jika kekeliruan dalam memahami persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang tidak relevan dalam skema presidensial ini terus berlanjut. Karena yang seharusnya diperdebatkan bukanlah ambang batas pencalonan presiden yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi dan basis dukungan parpol yang luas.Saatnya untuk membenahi dan mempertegas keberadaan UU Pilpres agar tidak hanya memfasilitasi para para elit parpol menjadi capres, namun turut membuka peluang agar munculnya calon-calon pimpinan alternatif terbaik untuk bangsa ini meski dari luar partai (independen). Jika tidak, pilpres yang berlangsung selama lima tahun sekali tidak akan menghasilkan perbaikan signifikan bagi kehidupan bangsa.
*Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan,
Pengamat Komunikasi Politik
Dani Fadillah*
Kala bangsa ini memerlukan sosok pemimpin alternatif yang dapat membawa bangsa ini keluar dari keterpurukan, sebuah fenomena unik terjadi, yaitu kesibukan anggota-anggota dewan di DPR yang tengah menggodok sebuah kebijakan yang menjurus pada seolah kualitas presiden ditentukan oleh besar-kecilnya dukungan parpol atas calon presiden. layaknya Pemilu Presiden 2009 dimana seseorang hanya bisa dicalonkan menjadi presiden dan wakilnya ketika mendapat dukungan paling sedikit 25% dari partai-partai pendukungnya secara nasional atau 20% kursi DPR. Kebijakan ini tertuang dalam UU No 42/2008 dan saat ini tengah diperbicangkan secara transaksional oleh DPR apakah persentasenya dikurangi atau malah diperbesar. Sebuah kebijakan yang menurut hemat penulis seharusnya tidak perlu dipersoalkan, lebih baik jika kebijakan itu dihilangkan saja.
Karena pemberlakuan ambang batas tertentu dalam pencalonan presiden sungguh tidak dapat diterima oleh akal sehat maupun dari segi kacamata politik. Begini, basis legitimasi presiden dalam sebuah negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Presiden dan parlemen adalah dua institusi yang berbeda dan memiliki basis legitimasi yang berbeda pula.
Singkat kata, pemberlakuan presidential threshold tidak dapat dijadikan sebagai standar batasan untuk pencalonan seseorang menjadi presiden nmaun dalam rangka menentukan persentase suara minimum sang calon presiden dinyatakan sahtelah terpilih untuk menjabat selama satu periode kedepan. Di Indonesia, kebijakan presidential threshold ini sudah sangat jelas bahwa Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Simpel, bukan?
Kebijakan tidak perlu semacam ini tidak perlu muncul seandainya para elit parpol tidak terperangkap ke dalam egoisme mereka. Beberapa partai besar mengusulkan ambang batas pencalonan presiden yang relatif tinggi karena terlalu percaya diri dengan elektabilitas masing-masing calon yang hendah mereka jagokan melalui hasil laporan lembaga survey kepercayaan mereka.
Dapat dikatakan tidak ada satupun elit partai yang berbicara soal kebutuhan kepemimpinan nasional dalam konteks krusial dan strategis untuk bangsa kita kedepan. Dan sangat minim ada parpol yang dengan jumawa mau mengakui ada sosok yang lebih oantas untuk memimpin bangsa ini yang berada diluar partainya jabatan sebagai ketua umum partai dengan dukungan matematis diatas kertas adalah syarat sah seseorang dicalonkan untuk menjadi presiden, bukan kualitas secara hakiki yang diakui dengan ksatria secara komunal.dan ujung-ujungnya Pilpres tak ubahnya ladang adu banyak uang untuk meraup suara sebanyak-banyaknya antar ketua umum parpol. Dalam pemaparan visi dan misi juga tidak akan diperjuangkan oleh masing-masing kandidat, dalam forum-forum debatpun hanya akan menjadi bumbu bahwa sekarang sedang dalam suasana pilpres.
Sungguh sangat mahal ongkos sosial dan politik yang harus ditanggung bansa ini jika kekeliruan dalam memahami persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang tidak relevan dalam skema presidensial ini terus berlanjut. Karena yang seharusnya diperdebatkan bukanlah ambang batas pencalonan presiden yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi dan basis dukungan parpol yang luas.Saatnya untuk membenahi dan mempertegas keberadaan UU Pilpres agar tidak hanya memfasilitasi para para elit parpol menjadi capres, namun turut membuka peluang agar munculnya calon-calon pimpinan alternatif terbaik untuk bangsa ini meski dari luar partai (independen). Jika tidak, pilpres yang berlangsung selama lima tahun sekali tidak akan menghasilkan perbaikan signifikan bagi kehidupan bangsa.
*Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan,
Pengamat Komunikasi Politik