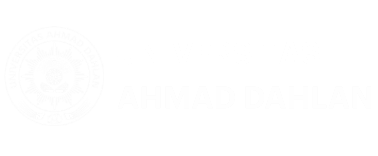Menghidupkan Kembali Budaya Lokal untuk Membangun Karakter
Dra. Alif Mua’rifah, S. Psi, M. Si
Pendidikan karakter mulai muncul dipermukaan begitu heboh pada puncak acara Hari Pendidikan Nasional 20 Mei 2010. Semua yang masih memiliki jiwa Nasionalisme harus bertanggungjawab terhadap keterpurukan mentalitas bangsa yang telah mencapai titik nadir (kehancuran). Pemerintah telah gagal dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yakni mengembangkan potensi anak didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia yang tertuang dalam pasal I UU Sisdiknas tahun 2003. Dimana keunggulan kualitas manusia tidak hanya terlihat adanya kecerdasan intelektual saja, melainkan harus dilihat dari keutuhan antara intelektual, emosional, sosial, dan moral serta spiritual (aspek cognitive, feeling dan action).
Banyaknya permasalahan yang menunjukkan rendahnya martabat bangsa telah terjadi pada hampir semua kehidupan dan begitu cepat meningkat, secara kualitas maupun kuantitas. Jika dilihat dari ahli Karakter Lickona (1992), bangsa kita telah masuk pada tebing kehancuran dengan berbagai gejala yang telah terjadi, yakni meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, kejujuran yang diselewengkan, menurunnya sikap hormat pada orangtua, guru maupun pemimpin. Meningkatnya konflik dan kebencian, memburuknya pemakaian bahasa, rendahnya etos kerja, rasa tanggungjawab yang rendah, meningkatnya perilaku perusakan diri serta kaburnya pedoman moral.
Keadaan tersebut dapat menjadikan manusia tidak memiliki martabat sebagai manusia (Ginsburg, dkk 1998; Planapl, 1999). Tebing kehancuran yang terlihat di depan mata bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dan melibatkan berbagai pihak.
Lemahnya sistem pemerintahan, ketidakjelasan hukum, pengaruh global sehingga mengikis budaya local yang dianggap tidak modern dan kuno. Padahal budaya lokal sangat kaya akan nilai kearifan serta memiliki prinsip universitalitas dan tidak bertentangan dengan ajaran agama serta budaya secara universal. Nilai lokal tersebut, dewasa ini tidak lagi dipakai sebagai patokan dan keteladanan dalam membentuk karakter anak, melainkan telah mulai terkikis oleh budaya asing yang mengarah pada individualistik, materialistik, serta kehidupan hidonisme.
Metode mendidik yang telah dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan ”3 ING” Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Prinsip memberikan contoh di depan, memberikan dorongan di tengah memberikan pengawasan di belakang tidak lagi diunggulkan sebagai pembentuk budi pekerti luhur. Banyak orang tua, guru, pemimpin telah hilang figur keteladanannya. Pelanggaran norma sudah bukan hal yang aneh, misalnya berperilaku tidak jujur mulai dari sederhana sampai yang kompeks. Orang tua dan guru TST mendukung anaknya agar saling menyontek dalam ujian atau ulangan, bahkan membuat trik agar anak melakukan hal tersebut dengan leluasa. Di rumah, orang tua berbuat sesuka hati, diantaranya melakukan pelanggaran disiplin, suka berbohong, tidak mampu mengendalikan emosi, suka mengumpat dan perilaku buruk lainnya.
Perilaku pemimpin yang banyak melanggar norma, kasus korupsi, manipulasi, pelecehan, kekerasan seksual serta pelanggaran hukum sudah menjadi habit yang kebal. Berbagai falsafah kearifan lokal lainnya seperti menang tanpo tanding, kalah tanpo nagsorake, ojo metani alane liyan, ono catur mungkur, mikul duwur mendem jero, lembah manah dan andap asor sudah mulai dipinggirkan dari peradaban manusia Indonesia. Ditambah peran media dengan berbagai informasi yang kurang mendidik dan kurang bertanggungjawab secara bebas menayangkan berbagai hal yang tidak semestinya menjadi konsumsi anak. Sedangkan prinsip terbentuknya perilaku menurut Ki Hajar Dewantoro adalah” 3 N” (Tri-no/nonton, niteni, nirokke untuk taman balita dan anak-anak, dan Tri-ngo/ngerti, ngroso, nglakoni, untuk usia ke atas. Ketiga ajaran tersebut merupakan model yang perlu dimiliki, dicontohkan oleh orang tua dan guru dan kemudian diajarkan kepada anak didiknya. Ketiga ajaran ini telah merangkum tiga unsur dalam aspek psikologis manusia, yakni aspek kognitif, afektif dan psikomotoris. Pada usia dini lebih banyak memberikan contoh setelah menginjak dewasa mengarah pada pemahaman dan pengertian. Baik Nontoni, niteni serta ngerti merupakan proses yang melibatkan kognisi sehingga menimbulkan kesan yang disimpan yang mendalam di dalam memorinya.
Ketika contoh dari orang dewasa sering dilihat bahkan diberikan penguatan oleh teman atau lingkungannya, maka kesannya semakin kuat. Apalagi jika contoh tersebut cocok dengan karakter dirinya maka ia akan mencoba mengikutinya. Jika orang tua, guru atau pemimpin sering melanggar norma, sangat tidak mungkin dapat melarang perilaku tersebut. Selanjutnya kemungkinan mengalami kegagalan dalam memberikan pengawasan di belakang. Oleh karena itu, sebaiknya dari mana pembangunan karakter dimulai??? Dari pembangunnya atau dari anaknya??? Sebagai salah satu pengamat dan pelaku pendidikan, maka tidaklah mungkin karakter dapat dibangun kembali dengan sepihak. Melainkan harus dilakukan dilakukan secara simultan. Pemerintah dengan pembenahan sistem, orang tua, guru, masyarakat, serta media. Sebab selama ini yang menjadi sasaran pembangunan karakter adalah siswa anak dan remaja. Sampai-sampai mendikbud kebingungan dan akhirnya dimasukkan pelajaran karakter dalam kurikulum di sekolah. Padahal para orang tua, guru dan pemimpin banyak yang lebih tidak berkarakter dibanding siswanya.
Pendidikan Karakter adalah tanggungjawab kita semua. Mungkin suatu ketika diperlukan sekolah bagi orang tua dan guru dan masyarakat untuk membenahi dan membangun karakter kembali agar bangsa ini tidak masuk dalam lubang kehancuran. Untuk itu, tak perlu kita bermimpi merubah dunia. Mari kita merubah diri sendiri, dengan mengembalikan nilai kearifan lokal yang telah dicontohkan oleh nenek moyang kita, ketauladanan budi pekertinya, sebagai bangsa yang santun, suka menolong dan rendah hati. Mengedepankan hati tanpa mengorbankan kecerdasan dan kewaspadaan. Mengukir akhlak melalui proses knowin the good, loving the good, and acting the good. Yakni, suatu proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan fisik, sehingga akhlak mulia bisa terukir menjadi habit of the mind, heart, and hands (Megawangi, 2007).
Penulis adalah Ketua Program Studi PGPAUD
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Ahmad Dahlan
Mahasiswa Social Science Universiti Sains Malaysia